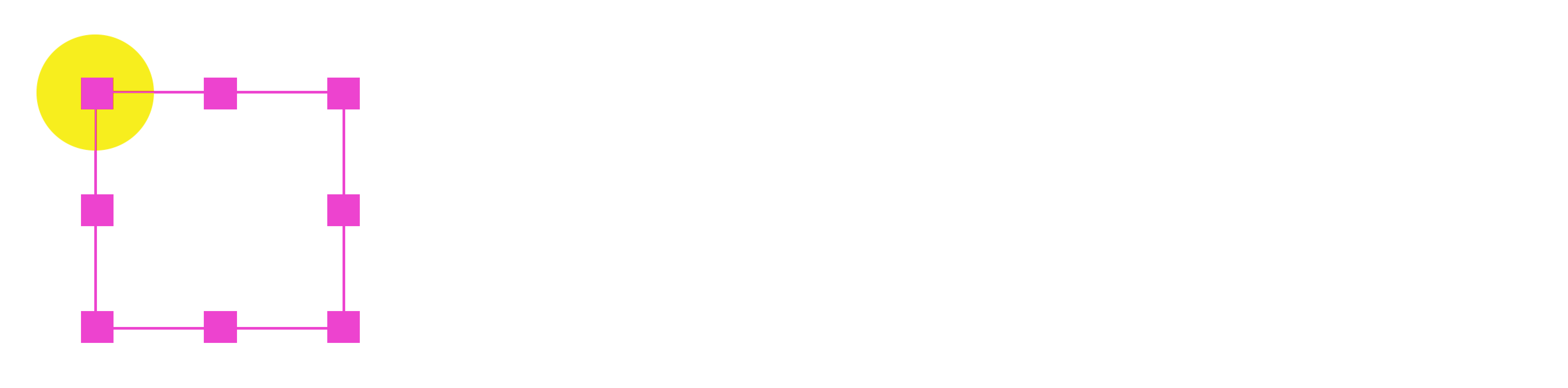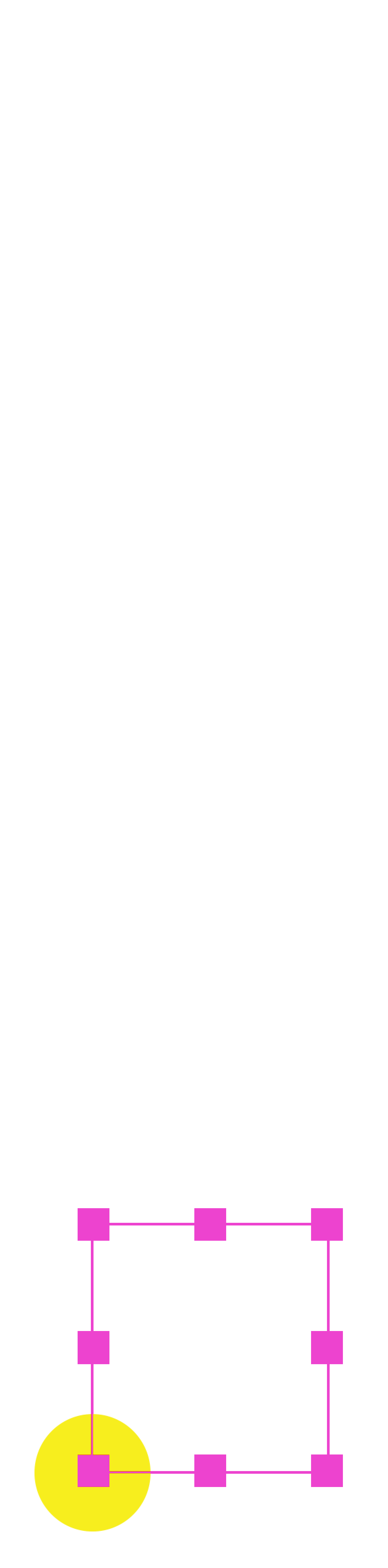Read in English Bali lambat laun tak hanya terkenal karena pariwisatanya, tapi juga kopi Fine…
Micro-Roastery Robusta di tengah Gelombang Ketiga
INDAH FEBRYYANI
Apa yang ada di pikiran anda ketika mendengar kata Robusta? Pahit? Kental? Laki? Kalau begitu, selamat! Anda termasuk dari banyak masyarakat Indonesia yang mengasosiasikan kopi, terutama Robusta, seperti tiga kata di atas.
Sebenarnya, bukan sebuah kesalahan ketika kopi Robusta menjelma menjadi kopi ‘laki’. Selama ratusan tahun terakhir, Robusta telah merajai pasar dunia. Diawali dar kopi bubuk sangrai hitam untuk kopi cepat saji yang menandai Gelombang Pertama, warga dunia perlahan-lahan mulai membentuk kecintaan terhadap kopi hitam nan legit dan kaya kafein ini. Namun semenjak satu dekade yang lalu, pasar specialti Arabika mulai naik daun dan merubah cara orang menikmati kopi.
Sekarang ini, Indonesia juga sedang bertransisi menjadi segmen kopi spesialti. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan kedai kopi spesialti yang bermunculan dalam 5 tahun terakhir. Istilah kerennya, Kopi Gelombang Ketiga. Berdasarkan laporan Financial Times dan Euromonitor pada Mei 2016, ada 1.083 gerai kedai kopi di Indonesia. Sebagian besar kedai, terkonsentrasi di area Ibukota. Euromonitor
memprediksi angka tersebut akan tumbuh sekitar 7% per tahun hingga 2020.
Tentu perkembangan kedai juga memacu naiknya tingkat konsumsi kopi. Berdasarkan data Statistik Perkebunan Indonesia pada tahun 2017, total produksi kopi mencapai angka 637.539 ton. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak konsumsi Robusta dari angka tersebut? Komposisi kopi Robusta kurang lebih 83% dan sisanya adalah kopi Arabika.
Loh, kok, ternyata di gelombang ketiga seperti ini, presentasi Robusta mengungguli total produksi Arabika?
Ternyata kalau dicermati lebih jauh ke hilir seperti Jakarta, ada banyak penyangrai kopi rumahan yang mengandalkan produknya di sektor Robusta. Salah satu area tersebut adalah Jelambar, Jakarta Barat. Ada kurang lebih tiga micro-roastery, dua diantaranya berfokus pada kopi Robusta dari Lampung, Sidikalang, Toraja, bahkan Aceh Takengon. Kualitasnya pun beragam mulai dari Fine Robusta sampai grade quality. Jakarta Timur juga memiliki skema yang sama yaitu berlokasi di Jatinegara. Masuk ke pelosok pasar Mester, kita akan disuguhi beragam pedagang kopi lokal yang melakukan proses produksi mikro dan sekali lagi banyak bermain dengan kopi Robusta. Toko kopi dan micro-roastery di area Jelambar rata-rata dikelola oleh warga Cina peranakan dan berlokasi di rumah yang disulap menjadi toko.

Berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pemilik micro-roastery di daerah Jelambar, yaitu Lim Kim Hoa atau biasa dipanggil Cik Lis, ada banyak cerita tentang geliat kopi lokal.
“Saya buka toko Aroma Prapatan udah hampir 38 tahun. Umur saya sekarang 80 tahun dan saya ngurus sendiri semua dari giling sampai kemas-kemasannya,” Cik Lis duduk sambil menunjukan deretan kaleng isi kopi-kopinya. Kalengnya sederhana, mirip seperti kaleng kerupuk warteg tetapi di cat biru muda dengan tulisan nama toko di badannya.

Ketika ditanya apakah bangkitnya pasar specialti Arabika berdampak kepada bisnisnya, Cik Lis hanya mengatakan bahwa permintaan untuk ground Robusta dalam beberapa tahun terakhir tetap stabil dan tinggi.
“Pasaran kopi Robusta sebenarnya cenderung lebih stabil. Dari tiga dekade saya jualan, mayoritas peminum kopi kita masih banyak mengonsumsi Robusta.”
Memang, meskipun dengan menjamurnya coffee shop dan berkembangnya sektor specialti Arabika yang mencari ciri khas kopi Origin, sebagian besar masyarakat di Jakarta masih adalah peminum kopi Robusta. Bayangkan orang tua kita dan generasi yang lebih tua, pekerja buruh, supir angkot, bahkan orang kantoran yang perlu tendangan-tendangan kafein beberapa kali sehari untuk dapat bekerja. Dengan kadar kafein yang hampir 50% lebih banyak dibanding Arabika, bagi sebagian besar masyarakat, ngopi adalah suatu kebutuhan.

Terkait segmen pasarnya, Cik Lis mengakui bahwa banyak pembelinya berasal dari peminum kopi rumahan. Selain untuk konsumsi pribadi, ada juga konveksi kecil yang membeli dalam partai besar untuk suplai minuman para pegawainya. Sisanya menjadi oleh-oleh khas ketika ada konsumen yang hendak pergi ke luar negeri.
Cik Lis melanjutkan, “Kopi Robusta lebih murah. Pembeli berani ambil banyak dan bisa dicampur-campur juga. Robusta kita ada dari Lampung sama Toraja, kalau Arabika yang bagus dari Toraja dan Medan.”
Malah, Jika kita tarik lebih panjang lagi, maka kita bisa melihat dampak yang besar, dari hulu ke hilir, jika pasar Robusta ini menyusut drastis. Di salah satu artikel Coffee Conversation kami , Adi Taroepratjeka menerangkan, “Tanpa adanya bisnis kopi jagung ini, harmonisasi kehidupan di industri kopi akan terganggu. Jika tidak ada lagi kopi jagung, berapa banyak petani kopi jagung yang kehilangan pekerjaan, begitu pula dengan para buruh pabrik kopi instan yang teramat banyak itu.” Dari sini bisa dilihat bahwa kopi Robusta memegang peranan ekonomi amat besar dari hulu ke hilir, sehingga sosoknya bukanlah sosok yang bisa dipandang sebelah mata.
Cik Lis pun mengaku bahwa dikarenakan ia memasok harga murah, ia tetap dapat meraup omset yang menggiurkan. “Sebulan saya bisa mengantongi cap tiao (sepuluh juta). Saya kan juga jualan cappuccino cincau, kalau digabung itu bisa jadi cap go tiao (lima belas juta). Total kopi yang berhasil terjual dalam sebulan rata-rata 50 kg, itu pun dalam kondisi penjualan yang standar. Penjualannya bisa meroket pesat saat musim lebaran atau natal.”

Siapa sangka sekelas micro-roastery seperti Cik Lis bisa membawa anak-cucunya sekolah dan tinggal di negeri tetangga dengan budaya kopi yang lebih maju. Anak kedua Cik Lis tinggal di Sydney, Australia bersama cucu serta cicitnya dan Cik Lis sendiri kerap berkunjung ke Australia dan menetap di sana selama sebulan setengah.
Sesekali mencicipi kopi spesialti di Australia tidak membuatnya minder dengan kualitas kopi yang dia jual. “Kopi saya enak ah, pahit. Dikasih susu juga makin gurih. Kalau di Australia enak juga, tapi lebih asem. Mesinnya lebih canggih.” Namun, Cik Lis tidak tergiur dengan mesin yang modern. Hingga sekarang, ia masih menggunakan mesin giling klasik buatan Cina yang dulu dibeli dengan harga Rp. 1.000.000.
“Mesin giling ada tiga. Tapi, sekarang nggak bisa giling lama-lama. Kalau kelamaan, dinamonya panas terus bau gosong. Jadi kalau sudah begitu kita gantian aja gilingnya dari satu mesin ke mesin yang lain, ngga masalah.”

Sekarang, Cik Lis juga menjual Arabika dengan harga Rp. 25.000/100 gm, angka yang sangat murah. Namun hal ini membuktikan bahwa Cik Lis hanyalah segelintir penggelut kopi yang tidak tergerus zaman pun terpengaruh modernisasi industri ini.
Berbagai macam ‘gelombang’ boleh datang dan pergi, namun bisnis rumahan semacam ini akan tetap langgeng tak termakan oleh waktu.
Baca juga, Petik Merah Saja: Kisah Gelang Merah dari Pangalengan.
Foto oleh penulis
INDAH FEBRYYANI, biasa dipanggil Nyo, adalah mahasiswi tingkat akhir jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Ia bisa ditemui di warung kopi lokal MAU Kopi & Minuman bersama suami.